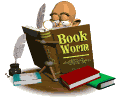
Bencana dan Pertolongan Psikologis
Bayangkan kita dan keluarga kehilangan rumah yang dibangun setelah kerja keras bertahun-tahun, tidak bisa dan tidak boleh lagi bermukim di lingkungan tempat tinggal yang rusak dan sangat berbahaya untuk terus ditinggali.
 Kita harus tidur berbulan-bulan di tempat penampungan bersama ratusan orang, anak luka cukup parah, dan kita sama sekali tidak punya bayangan tentang masa depan. Sangat wajar bila menjadi sangat galau dan mudah tersulut hal tidak berkenan, seperti orang tidak antre, ada kecurangan, dan merasa diobyekkan orang luar.
Kita harus tidur berbulan-bulan di tempat penampungan bersama ratusan orang, anak luka cukup parah, dan kita sama sekali tidak punya bayangan tentang masa depan. Sangat wajar bila menjadi sangat galau dan mudah tersulut hal tidak berkenan, seperti orang tidak antre, ada kecurangan, dan merasa diobyekkan orang luar.Pertolongan pertama psikologis
Teman saya, Nael, dalam diskusi milis psikologi mengusulkan kita bertanya kepada diri sendiri: ”Kalau saya jadi penyintas (survivor), apa yang saya inginkan orang lain lakukan kepada saya sehingga merasa terbantu mengatasi situasi yang sangat menghancurkan hati ini?”
Yang terpenting adalah memahami situasi, berhubungan, dan memberi dukungan dengan menghormati martabat dan harga diri penyintas. Untuk pertolongan pertama, pendekatan penyintas ”sakit psikologis” dan perlu segera ”konseling trauma” sebaiknya ditunda dulu. Bukankah saat krisis siapa pun sedang menyesuaikan diri dengan kehilangan dan kondisi hidup yang sangat berubah? Orang luar yang tidak dapat sepenuhnya merasakan apa yang terjadi perlu memberi ruang karena sebagian besar manusia memiliki mekanisme adaptasi alamiah yang memungkinkan ia menghadapi, mengelola, dan bangkit dari persoalannya.
Relawan sosial dan psikologi baik bila dapat terlibat dalam kerja awal, seperti distribusi makanan dan membantu mengelola luka fisik, untuk dapat sungguh memahami situasi, bukan segera melakukan ”konseling trauma”. Tujuannya agar pada tahap berikut dapat memberi dukungan psikologis dengan pendekatan tepat.
Pertolongan psikologis fase awal yang membantu adalah normalisasi, yaitu menyadarkan reaksi psikologis yang muncul pada penyintas adalah hal normal dan wajar, juga langkah mengembalikan rutinitas dan struktur keseharian untuk meminimalkan rasa tak berdaya dan frustrasi. Kita ada sebagai teman untuk mendengar, melakukan hal mendesak yang sementara waktu tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyintas/keluarga. Sekaligus tetap memastikan pemandirian, tidak memberikan dukungan yang justru menciptakan ketergantungan.
Pekerja media
Perhatikan betapa kita merasa nyaman dengan penayangan berita pascabencana oleh reporter yang menampilkan empati, bersikap menjadi bagian dari masyarakat yang sedang diliput yang berarti tampil sederhana, apa adanya, peduli, tidak dibuat-buat, dan tidak mengobyekkan.
Menjunjung tinggi penghormatan kepada korban atau penyintas bencana sebagai manusia bermartabat tidak menjadikan masyarakat sekadar obyek berita dan kompetisi pemberitaan media. Bayangkan apa yang kita rasakan ketika reporter tampil penuh bangga dan senyum, dengan gaya sangat percaya dan puas diri, seolah bencana menjadi ajang tampil prima saat melaporkan kejadian.
Mengingat masyarakat Indonesia harus selalu bersiap menghadapi bencana, media perlu menyediakan berita dan informasi yang membangun kesadaran, solidaritas, dan rasa berdaya, dengan fokus pada how to. Media dapat melakukan banyak hal untuk menguatkan masyarakat melakukan langkah konkret pencegahan dan penanganan, misalnya menjelaskan struktur bangunan tahan gempa dalam bahasa sederhana, langkah tanggap darurat di komunitas, pemastian distribusi bantuan fisik yang merata, dan bagaimana mendampingi anak di masa sulit.
Siapa dapat membantu?
Siapa saja dapat memberi dukungan, dengan peran berbeda-beda. Saat di lapangan, relawan, pekerja kemanusiaan, dan masyarakat sendiri dapat melakukan identifikasi mengenali kelompok kecil atau individu tertentu yang perlu dibantu psikolog profesional. Mereka, misalnya, yang masih sangat dikungkung trauma, sementara masyarakat sekitar secara umum sudah dapat lebih baik beradaptasi.
Mungkin ada yang tampil dengan perilaku tidak lazim, menjadi agresif, sangat menarik diri dan takut, tidak dapat lagi menjalani aktivitas harian seperti sebelumnya. Untuk lanjutan, psikolog klinis dan psikiater dapat lebih membantu. Pendekatan paling efektif adalah tidak hanya mendeteksi masalah/keluhan/tanda distres saja, tetapi juga melihat potensi individu, kelompok dan praktik budaya dan potensi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dukungan psikologis bagi komunitasnya.
Kita juga perlu memberi perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, khususnya terkait perlindungan atas reproduksi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keamanan diri. Juga memastikan tiadanya diskriminasi atau peminggiran terhadap kelompok rentan lain, seperti penyandang cacat, kelompok termiskin, dan kelompok yang dikenai stigma, misalnya penyandang gangguan jiwa.
Pada akhirnya, dukungan psikologis kurang bermakna bila tidak diintegrasikan dengan dukungan fisik, perbaikan sarana-prasarana, fasilitasi pengembangan mata pencaharian baru, dan lain sebagainya.
Benar sekali pendapat seorang penyintas: ”Kami tidak perlu macam-macam, yang penting kami dibantu dapat kembali tinggal dalam rumah yang layak dan memperoleh pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Bila kami tinggal diam terus menadahkan tangan dalam suasana ketidakpastian dan penuh kejenuhan, memang kami bisa jadi ’gila’!”
Semoga kita, terutama pengambil kebijakan, memiliki sense of crisis dan dapat mengambil tindakan tepat, tidak terus-menerus terlambat, saling menunggu, apalagi saling menyalahkan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Nomor arsip | - 261009-PIR-AL02-0004 |
| Judul | - Bencana dan Pertolongan Psikologis |
| Karya | - Kristi Poerwandari |
| Tentang penulis | - Psikolog |
| Sumber | - kesehatan.kompas.com |
| Link | - Klik disini |
| Publikasi | - Pustaka Indonesia Raya |
| Pesan kami | - Kunjungi situs resmi untuk melihat topik menarik lainnya |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~